Dalam 'rumah kaca' korporasi dan pemerintah
'99,9 persen benih transgenik dikuasai 6 perusahaan multinasional, di mana Monsanto menguasai 90 persen.'
(Guru Besar Fakultas Pertanian Insitut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa)
Suryo Adi Pramono
Pada 28 Januari 2025 malam Mbah Gondrong (bukan nama sebenarnya) menyampaikan secara singkat budidaya padi dan jagung yang dilakukannya di angkringan Mas Pothon (nama panggilan Mas Triyono). Lokasinya di utara Jogja Bay, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanpa menguraikan, Mbah Gondrong menyampaikan bahwa ia sekarang tengah menanam jagung kuning dengan benih P 40 (produk pabrik) atas usulan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang rutin tiap bulan datang di pertemuan petani Padukuhan Malangrejo.
'Tetapi hasilnnya kurang baik. Ternyata bulir jagungnya kecil-kecil; tidak besar-besar. Jadi isinya kurang,' kata Mbah Gondrong dalam Bahasa Jawa yang lalu saya terjemahkan pada tulisan ini.
'Jagungnya itu digunakan untuk pakan atau dikonsumsi konsumen?', tanya saya.
'Ya dijual untuk pakan ternak. Nanti jagung itu digunakan untuk campuran pakan ternak, dicampur dengan konsentrat dan lainnya, yang sudah ada formulanya sendiri menurut pengusaha,' penjelasannya.
'Setahun menanam jagung berapa kali, mbah?', tanya saya.
'Ya sekali. Saya dan temen-teman menanam ya padi-padi-jagung. Begitu urutannya dalam setahun. Bila masih banyak air para petani menanam padi, tetapi bila airnya telah berkurang, ya semua menanam jagung,' ia menambahi penjelasan.
'Dari hasil panen jagung itu apakah dapat membuat benih sendiri untuk penanaman selanjutnya?', tanya saya.
'Ya beli lagi. Karena bila membuat benih sendiri itu kata PPL nanti tidak tahan hama. Jadi ya dijual semua terus ketika akan menanam ya membeli benih kambali,' katanya.
Demikianlah, petani selalu membeli benih jagung dan menjual hasil panennya untuk pakan ternak.
Dalam obrolan di angkringan malam itu Mbah Gondrong menyampaikan bahwa pembelian benih dengan menggunakan Kartu Tani. Melalui kartu ini, pengurus kelompok tani dapat mengetahui berapa anggota yang akan membeli benih jagung secara bersama-sama. Tanpa Kartu Tani maka PPL tidak akan melayani pembelian bersama sehingga petani harus membeli sendiri benih jagung dengan pergi ke toko pertanian.
Bukan hanya benih pabrikan, Mbah Gondrong juga menggunakan urea buatan pabrik untuk memupuk tanaman jagungnya.
'Menggunakan pupuk kandang, tidak mbah?', tanya saya.
Ia menjawab, 'Menggunakan, tetapi jarang-jarang. Paling 3 tahun sekali. Itu saja tidak merata. Jadi diselang-seling. Umpama tahun ini sebelah sini, lain waktu sebelah yang lain. Nanti ya akan merata sendiri.'
Mbah Gondrong tidak mempunyai ternak sehingga ia harus membeli kotoran hewan untuk membuat pupuk kandang.

Ia menceritakan bahwa ia menggunakan pupuk Phonska pula untuk mengimbangi pupuk urea karena pupuk urea mengakibatkan tanah menjadi keras. Selain menyuburkan pertumbuhan tanaman pupuk urea ternyata membuat tanah bantat, padat atau keras sehingga pori-pori tanah tertutup. Akibatnya oksigen tidak dapat menembus tanah dan akar tanaman kekurangan oksigen. Ketika penyiraman air dilakukan, tanah bantat membuat air tak semua dapat meresap ke dalam perakaran. Sebaliknya, bila tanah bantat itu terjadi di sekitar perakaran maka ketika air mengaliri maka ia tergenang pada perakaran, yang bila tidak dapat meresap ke dalam tanah dan diserap oleh akar maka akan menyebabkan akar selalu basah sehingga bisa berisiko menjadi busuk dan kemudian tanaman mati.
Hal serupa pernah saya dengar pada tahun 2009 di Mbangan, Desa Sidorejo, lereng tenggara Gunung Merapi. Pak Riyanto bercerita bahwa ia mengamati tanahnya menjadi keras akibat pemakaian pupuk pabrikan. Akar tanaman susah menembus ke bawah untuk mencari makanan dari unsur-unsur hara yang tersedia. Fungsi tanah hanya untuk menegakkan tanaman tumbuh tetapi kesuburannya tergantung pada pupuk urea yang diberikan.
Ketika air masih banyak, seperti pada musim penghujan dan ketika air Embung Pajangan masih mencukupi, Mbah Gondrong menanam padi. Bila jagung berumur 4 bulan untuk bisa dipanen maka panen padi memiliki usia lebih pendek, sehingga ia bisa menanam padi dua kali setahun. Sekarang, jenis padi PP yang ia tanam sebagai ganti jenis padi 64.

Apa yang Mbah Gondrong lakukan dengan budidaya jagung dan padinya mengingatkan saya pada Minggu, 26 Januari 2025, ketika sengaja melewati kawasan perdesaan di pedalaman Pegunungan Kendeng dalam perjalanan dari Pati ke Solo (Jawa Tengah). Perkebunan jagung di Desa Kemadohbatur yang berkontur tanah pegunungan kapur naik turun itu tengah panen jagung. Jagung warna kuning itu adalah jagung hibrida yang benihnya dibeli dari pabrik. Lahan kering memang cocok untuk tanaman jagung. Persis seperti kata Mbah Gondrong, ”Kalau jagung itu tidak memerlukan banyak air. Berbeda dari padi.” Di angkringan itu saya kemudian tersadar mengapa banyak jagung ditanam di Kemadohbatur, ya karena lereng Pegunungan Kendeng itu kawasan tanah kering yang berlapis kapur. Justru di kawasan kering inilah para petani di desa itu memanfaatkannya, sehingga di hamparan luas sejauh mata memandang itu nyaris semuanya adalah tanaman jagung yang sudah dipanen sehingga batangnya rebah.
Pada beberapa tempat saya melihat tandon air di area peternakan ayam yang dugaan saya airnya diambil dari sumber air artesis yang sangat dalam dan mahal biaya pengeborannya. Pelaku usaha ini besar kemungkinan orang kaya, atau didukung dana investor. Lahan jagung dan peternakan ayam memang saling membutuhkan: penyedia pakan dan butuh pakan, di samping kotoran ayam dapat dijadikan pupuk kandang dengan proses fermentasi tertentu bagi petani.

Di Pegunungan Kendeng itu saya mengamati ada jagung yang ditanam di sela-sela pohon kayu putih. Di beberapa lahan lain, jagung ditanam di lahan samping rumah. Ada pula jagung ditanam di sela-sela tanaman jati yang masih muda dengan ketinggian antara 1,5 - 2 meteran sehingga cahaya matahari masih dapat menyinari. Oleh karena di hamparan terbuka, dan pohon kayu putih yang ditanam Perhutani hanya sekitar 2 meteran, dan jarak tanamnya pun berjauhan, maka di sela-sela itu tanaman jagung dapat tumbuh. Petani yang berlahan cukup luas menanam padi dengan sistem tumpangsari dengan jagung. Pada sisi tepi dan dekat pematang sawah ia tanam jagung, sedangkan di bagian tengah ia tanami padi.
Bu Warti, panggilan untuk Suwarti, memperjelas informasi bahwa petani yang menanam jagung di lahan Perhutani adalah mereka yang memiliki sanggeman. Sepengetahuan saya, berdasarkan riset di Lereng Gunung Merapi (2008-2010), sanggeman adalah kerjasama antara Perhutani dan petani di sekitar pinggir hutan dengan ketentuan bahwa petani harus turut merawat tanaman Perhutani dengan imbal-balik mereka boleh memanfaatkan lahan kosong di sela-sela tanaman Perhutani itu untuk bercocok-tanam dan mengambil ranting-ranting kering yang jatuh dari pepohonan yang Perhutani tanam. Luasnya lahan dan banyaknya produksi jagung di kawasan ini mendorong salah seorang pajabat pemerintah Kabupaten Grobogan menyatakan bahwa kabupatennya siap menjadi lumbung jagung untuk mendukung program nasional pemerintah.

Pertanian jagung ini ternyata memunculkan pekerjaan lain, misalnya usaha perontok jagung, angkutan (truk dan mobil pick up), bengkel kendaraan, buruh tani, toko pertanian (menyediakan benih tanaman, pupuk dan pestisida, di samping peralatan pertanian), usaha ternak ayam (yang berdekatan dengan lahan pertanian jagung sehingga pasokan pakan terjamin), buruh tani, dan para pengepul hasil panen (yang akan menjual panen jagung ke pabrik pakan ternak dan peternak besar). Sirkulasi ekonomi tumbuh di areal pegunungan kapur itu.
Meskipun panen mereka bagus tetapi petani tidak memproduksi benih dan pupuk tanaman sendiri; berbeda dari format pertanian organik. Petani tinggal menggarap lahan, menanam, merawat, menanam dan menjual hasil panennya. Kata Bu Warti, umumnya para petani menggunakan kombinasi antara pupuk kandang, urea dan phonska untuk merawat kesuburan tanaman dan tanah mereka. Oleh karena itu, toko pertanian hadir di kawasan ini, demikian pula jaringan pengadaan benih tanaman, padi dan jagung.
Hal ini saya temui juga di Desa Asem Gedhe (Jombang utara, berbatasan dengan Lumajang), Semen (lereng timur Gunung Wilis, Kediri), dan lereng Gunung Arjuna (persis di bawah Jatim Park 1) ketika menelusuri keberadaan benih lokal di Kabupaten Jombang, Kediri, Mojokerto dan Pasuruan. Ini diamati pada tahun 2019 dalam rangka riset Aliansi Organis Indonesia (AOI). Benih lokal terdesak oleh keberadaan benih pabrikan, yang kebanyakan berjenis hibrida, sehingga benih yang dihasilkan tidak dapat menghasilkan jagung kembali; hanya daun lebat. Pupuk kandang pun terdesak oleh pupuk pabrikan.
Ancaman hukum
Petani yang berhasil memuliakan benih dan kemudian menjualnya ternyata harus berhadapan dengan hukum karena dinilai melanggar ketentuan. Petani di Aceh dan Kediri pernah mengalami ancaman hukum ini, meskipun sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Orde Baru. Mereka biasa menghasilkan benih secara mandiri untuk keperluan budidaya sendiri, para tetangga dan orang lain yang membutuhkan. Ketentuan hukum menyatakan bahwa benih yang diperjual-belikan harus sudah melalui proses laboratorium, pelepasan benih dan berijin distribusi. Itu semua hanya bisa dilakukan oleh korporasi; bukan koperasi petani, apalagi petani perorangan.
Selama proses hukum berjalan, korporasi dan aparat pemerintah terkait berhadapan dengan petani, advokat mereka dan LSM sampai tingkat Mahkamah Konstitusi (MK). Advokasi mengarah pada pasal tertentu yang dipandang bertentangan dengan UUD 1945. Menurut penuturannya, Mbah Gatot, petani organik di Purbalingga, turut bersaksi di depan majelis hakim tentang hal ini karena ia pun menggunakan benih sendiri untuk menanam padi.
Aliansi LSM menulis pembelaan advokatif dengan berargumentasi bahwa benih tidak dapat dikuasai oleh pihak tertentu atas dasar ketentuan hukum karena secara genetik, benih memiliki caranya sendiri untuk beradaptasi dan berkembang di luar upaya manusia secara alamiah. Oleh karena itu, pemuliaan benih tdak bisa secara monopolistis dimiliki oleh perusahaan tertentu melalui hak paten. Silang argumentasi ilmiah dan hukum itu akhirnya berujung pada keputusan MK, bahwa petani boleh melakukan pemuliaan benih tetapi untuk keperluan sendiri dan kelompok taninya tanpa dimaksudkan untuk didistribusikan ke pasar benih, bila tidak melalui proses pelepasan benih menurut aturan perundangan dan dilakukan oleh korporasi yang memiliki legalitaas untuk melakukannya. Para petani yang sempat ditahan oleh polisi kemudian dilepaskan dan kembali sebagai petani pemulia benih.
Pasca kasus itu, bersama Tim AOI, saya pernah mengunjungi Pak Heru di Kediri. Meskipun ketentuan hukum memperbolehkan petani menghasilkan benih, Pak Heru masih secara sembunyi-sembunyi bereksperimen dan mendistribusikan benih yang berhasil dimuliakannya. Pak Heru menyatakan bahwa upayanya itu untuk membantu petani agar bagus hasilnya.
Di pinggiran barat laut Kediri, saya menanyai petani yang sedang menanam jagung dengan benih pabrikan terkenal. Ternyata hasilnya pun tak selalu bagus; tak ada jaminan bahwa kualitas benih hasil pabrikan selalu bagus hasil panennya.
Pabrik melakukan riset dengan menggunakan tenaga para petani yang mereka bayar, seperti yang Tim AOI temui di pinggiran sebuah padukuhan di barat laut Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Perusahaan kemudian mematenkan hasil kerja para petani pemulia benih itu dan kemudian memasarkannya secara legal. Inilah kelebihan legal standing, akses ke pengambil kebijakan, modal, dan jaringan yang dimiliki oleh korporasi dibandingkan para petani baik kolektif maupun perorangan.
Dalam kaitan itu, berikut beberapa korporasi besar yang memproduksi benih, pupuk dan pestisida untuk petani Indonesia:
- PT Pupuk Indonesia (Persero): Pemilik beberapa anak perusahaan, misalnya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP), PT Petrokimia Gresik (PKG), dan PT Pupuk Kujang (PKC)
- PT Pupuk Indonesia Pangan: Penyedia pupuk, pestisida, dan bimbingan teknis pertanian
- PT Saprotan Utama: Produsen swasta nasional dan penyalur pupuk, pestisida, dan benih
- PT East West Seed Indonesia (EWINDO): Produsen benih sayuran berkualitas tinggi
- PT BISI International Tbk (BISI): Produsen benih hibrida jagung, padi, dan hortikultura
- Syngenta Indonesia: Perusahaan produsen benih dan produk perlindungan tanaman
- PT Kencana Artha Raya: Perusahaan trading agribisnis penyedia benih dan pupuk
Berkaitan dengan femomena itu, sebuah media massa mengutip pendapat pakar pertanian, bernama Dwi Andreas Santosa, seorang guru besar IPB dan Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), yang menyatakan:
'Tak hanya hulu, tapi hilir juga dikuasai perusahaan multinasional. Lantas, mau ke mana arah pertanian kita ke depan?' kata Guru Besar Fakultas Pertanian Insitut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa pada diskusi, Rabu (18/12/2013). Lebih lanjut, Andreas menjelaskan dari sisi hulu, 100 persen kepemilikan saham perusahaan yang memproduksi pestisida dikuasai perusahaan asing. Adapun bidang benih (seed), 100 persen benih beras inbrid dikuasai BUMN. 90 persen benih beras hibrida, 90 persen benih jagung hibrida, dan 70 persen benih hortikultura dikuasai multinasional. Adapun untuk pupuk, 70 persen dikuasai perusahaan Indonesia dan 30 persennya dikuasai multinasional,' jelas dia.
Pak Andreas juga menyatakan bahwa kondisi tersebut terjadi pula secara global karena sebesar 90 persen perdagangan pangan dikuasai 5 perusahaan multinasional. Sebesar 89 persen input pertanian (agrokimia) didominasi oleh 10 perusahaan multinasional, sedangkan 67 persen pasar benih dikuasai oleh 10 perusahaan multinasional. Ia mengatakan, 'Jadi, 99,9 persen benih transgenik dikuasai 6 perusahaan multinasional, di mana Monsanto menguasai 90 persen.' Kisah pada awal tulisan ini menunjukkan bahwa gambar makro itu terkonfirmasi oleh kisah para petani kecil di berbagai daerah.
Paparan di atas menunjukkan penguasaan korporasi terhadap kehidupan petani. Sektor input dan output dikuasai oleh korporasi, sedangkan petani hanya menjadi 'tenaga kerja' sektor pertanian karena hanya melakukan budidaya. Aneka keterampilan nenek moyang tentang membuat benih, pupuk dan ramuan anti-hama serta menentukan harga jual hasil panen di pasar tidak lagi mereka kuasai. Semua harga ditentukan pabrik, demikian pula hasil panen.
Swasembada pangan
Secara historis hal ini bermula ketika pemerintah Orde Baru hendak mengatasi kekurangan pangan setelah menggantikan pemerintahan Soekarno pada pertengahan tahun 1960-an. Mas Ngadiono, tetangga di Pogung Dalangan, Sinduadi, Sleman, DIY, pernah bercerita bahwa ia berjalan kaki ke Kentungan (Jalan Kaliurang Km. 6) untuk membeli beras. Ia antre lama di tempat antrean namun ketika ia sampai di depan untuk membeli beras ternyata beras sudah habis dan kemudian ia harus kembali ke tempat itu lagi keesokan harinya untuk berupaya kembali membeli beras tersebut. Itu terjadi ketika pemerintahan Bung Karno. Kisah seperti yang Mas Ngadiono alami mungkin dialami pula oleh banyak warga pada sekitar pertengahan dekade 1960-an. Inilah tantangan Rezim Soeharto di awal berdirinya.
Oleh karena itu, Pak Harto memanfaatkan Revolusi Hijau untuk mencukupi kebutuhan pangan. Hasil penelitian International Rice Research Institute (IRRI) di Los Banos, Filipina, dipakainya untuk memajukan pertanian Indonesia. Ia mencanangkan program ketahanan pangan dan kemudian swasembada pangan sejak akhir tahun 1960-an. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dilakukan di bawah slogan 'Modernisasi Desa'. Panca Usaha Tani digalakkan untuk mendukung intensifikasi pertanian. Sementara itu, mekanisasi pertanian dan irigasi digunakan untuk ekstensifikasi pertanian. Penggunaan bibit padi IR 36 dari IRRI, penggunaan pupuk pabrikan (urea, phonska, ZA, NPK), dan aneka pestisida dimaksudkan untuk memastikan keberhasilan panen. Pembangunan waduk, saluran irigasi dan penerjunan PPL ke desa-desa menopang usaha itu dari sisi infrastruktur dan SDM sektor pertanian. Di perguruan tinggi, Fakultas Pertanian didukung oleh pendirian Fakultas Teknologi Pertanian yang di dalamnya ada Jurusan Mekanisasi Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian. Kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian agar kelaparan dan kekurangan pangan tidak lagi terjadi seperti era Orde Lama.
Apakah di lapangan hal itu berjalan dengan mulus? Cak Toko, aktivis AOI di Trawas, Mojokerto, menceritakan bahwa dulu para petani tidak mudah untuk menerima program pemerintah itu. Untuk mengefektifkan, pemerintah terpaksa menggunakan tentara untuk turut mempersuasi, untuk tidak mengatakan “memaksa”, petani agar mau menanam sesuai dengan anjuran pemerintah. Ketika itu, para petani masih menggunakan pupuk kandang, benih sendiri dan berorientasi subsisten. Bila ada kelebihan hasil panen maka mereka baru menjualnya ke pasar, atau barter dengan bahan kebutuhan lain yang tetangga miliki. Tindakan represif itu membuahkan hasil karena para petani kemudian secara berangsur melakukan aneka kegiatan Panca Usaha Tani itu.
Benih padi IR 36 dipakai luas di banyak tempat, demikian pula aneka pupuk anorganik dan pestisida. Petani pun senang karena dapat melakukan panen tiga kali dalam setahun, berbeda dari waktu sebelumnya yang hanya panen dua kali setahun. Namun demikian, identitas pertanian lokal, seperti padi Bandhul Wesi, misalnya, tidak ada lagi yang mau menanam karena masa tanamnya lama, yaitu sekitar enam bulan. Bapaknya Cak Toko menyatakan:[1]
'Wah…sesungguhnya ya kecewa ya mas. Sekarang padi Bandhul Wesi sudah tidak ada. Benihnya telah habis karena lama tidak ditanam lagi. Sebenarnya dapat dijadikan ciri khas produk kampung sini. Bulir padinya memang mantap. Jadi mereka yang memanggul ya merasakan betapa beratnya panen padi itu, karena memang sungguh berbobot. Nasinya juga enak, tetapi ya memang lama menanamnya, bisa sampai enam bulan. Yang membuat enak itu ya karena lama menanamnya, ya mas.'
Namun lokalitas benih padi bukanlah prioritas pemerintah. Pemerintah memerlukan padi dengan produktivitas tinggi agar ketahanan pangan tercapai.
Pada tahun 1983 swasembada pangan dapat diraih oleh Pemerintahan Soeharto setelah berupaya lebih dari satu dekade. Oleh FAO, Presiden Soeharto dinilai sebagai pemimpin yang berhasil membawa Indonesia dari negara yang berkekurangan pangan menjadi berkecukupan pangan, bahkan dengan cara swasembada pangan. Pak Harto pun diundang ke sidang FAO untuk berpidato tentang capaian dan cara keberhasilan pertanian yang dilakukan. Pak Harto memperoleh penghargaan kelas dunia dan menjadi contoh bagi negara-negara lain.
Namun cerita belum 'happy ending'. Pada tahun berikutnya, hama wereng merajalela. Dalam diskusi tentang pertanian organik yang diselenggarakan kerjasama antara Universitas Passau (Jerman), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Institut Pertanian Bogor dan AOI di Yogyakarta pada 2019, salah seorang pembicara dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa orang-orang di sekitar Pak Harto gundah akan hal itu. Wereng harus ditanggulangi tetapi mereka takut menyampaikannya kepada Pak Harto. Oleh karena itu, mereka mencari cara agar ada orang yang mau membantu dan menyampaikan dengan cara tertentu kepada Pak Harto tanpa membuatnya marah. Singkat cerita, Pak Harto akhirnya tahu, kemudian program pemberantasan hama wereng dilakukan, bersama dengan peningkatan kualitas benih padi.
Kita tahu pada tahun-tahun sesudah itu, jenis benih padi Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW) berhasil ditemukan dan kemudian didistribusikan di seluruh pelosok pertanian Indonesia. Pestisida, insektisida dan herbisida digalakkan bersama dengan benih padi VUTW itu. Panca Usaha Tani yang mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian pun mengintegrasikan diri dengan penanaman benih padi VUTW itu. Aneka sekolah lapang pertanian pun digalakkan untuk melatih banyak relawan dan PPL yang akan mendampingi petani dalam berbudidaya.
Meskipun semua usaha dilakukan, tetapi swasembada pangan tak lagi dengan mudah dipertahankan. Impor beras masih dilakukan oleh Rezim Soeharto hingga ia dilengserkan pada 21 Mei 1998. Ini semua terjadi setelah krisis moneter (“krismon”) melanda dan demonstrasi mahasiswa antarkota yang masif, serta para orang dekatnya mengundurkan diri. Pasca Rezim Soeharto, di Era Reformasi, Indonesia masih mengimpor beras, selain jagung dan kedelai.
Diversifikasi pangan pun digalakkan agar warga tidak hanya mengkonsumsi beras. Namun hal ini tidak mudah. Warga Maluku dan Papua, serta NTT, misalnya, juga mengonsumsi nasi, bukan lagi sagu dan jagung atau sorgum, sebagaimana saya saksikan ketika berkunjung ke Ambon dan Larantuka sebelum Covid-19 melanda. Sagu disajikan di Ambon sebagai hidangan sampingan, tetapi makanan pokok mereka juga nasi. Namun di lereng Gunung Arjuna, nasi yang dicampur dengan potongan ketela pohon manis dan jagung manis (nasi empok) menjadi makanan sehari-hari untuk mengatasi keterbatasan persediaan beras, yang menurut saya, enak juga rasanya.

Ketahanan pangan tidak dapat diraih secara swasembada tetapi dengan topangan impor dari luar negeri sampai hari ini. Bila petani tergantung pada korporasi dan pemerintah, maka pemerintah pun tergantung pada impor pangan dari beberapa negara lain dalam memenuhi ketahanan pangan warga negara. Ironisnya, di Kasepuhan Ciptagelar dan Tanah Sunda justru mandiri pangan dengan pertanian organik berbasis kearifan lokal yang mereka pertahankan.
Perlawanan gerakan pertanian organik
Michel Foucault pernah menyatakan bahwa relasi kuasa dapat berlangsung di mana saja. Dalam sebuah buku berisi wawancara, Power/ Knowledge (1980, hal.247), editornya Colin Gordon menulis, 'Foucault's thesis of the omnipresence of relations of power or power/ knowledge is all too easily run together with the idea that all power, in so far as it is held, is a kind of sovereignty amounting to untrammelled mastery, absolute rule or command.' Di timur Gunung Slamet, Jawa Tengah, Mbah Gatot Surono pernah mengalami bagaimana relasi kuasa tersebut dalam kehidupannya sebagai petani, demikian pula pada pemulia benih di atas. Ia dipaksa tunduk oleh kuasa dan pengetahuan yang dikomandokan oleh aparatus kekuasaan sewaktu menanam jenis padi dengan cara budidaya yang berbeda dari instruksi pemerintah. Simbah yang berusia lebih dari 80 tahun ini yang tinggal di Bukateja, Purbalingga, bercerita kepada kami pada 2019 bahwa tanaman padinya pernah dicabuti oleh sejumlah tentara karena ia menanam benih padi Rojolele yang dibawanya dari Juwiring (Klaten, Jawa Tengah) secara organik (tanpa pupuk dan pestisida kimia) yang berbeda dari kebijakan pemerintah. Untung padi yang dicabuti itu hanya diletakkan di tepi sawah yang ia sewa. Ia kemudian menanamnya kembali. Singkat cerita, selang beberapa bulan kemudian, padi itu pun menguning dan berhasil panen.


Dengan menggunakan beras hasil panen itu, istrinya dimintanya menanak nasi yang agak banyak dan memasak sayur serta lauk yang enak. Ia kemudian meminta tolong anggota keluarganya untuk mengundang para tentara dan komandannya di komando rayon militer (koramil) setempat. Setelah semua tamu itu hadir, ia kemudian menyatakan bahwa hari ini istrinya memasak agak banyak dan mengundang bapak-bapak tentara dan komandannya untuk makan bersama di rumahnya. Setelah makan selesai, ia bertanya kepada mereka,
'Bapak-bapak, bagaimana rasa nasi yang dihidangkan istri saya?'
Mereka menyatakan bahwa rasanya enak; berbeda dari nasi-nasi pada umumnya. Ditambah sayur dan lauk yang pas dan enak, maka makan siang itu sungguh nikmat, kata mereka.
Mbah Gatot lalu menyambung,
'Nasi yang bapak-bapak makan itu berasal dari padi yang dulu bapak-bapak cabut dari sawah. Untung mereka masih bisa hidup dan tumbuh lagi, sehingga hasil panennya dapat kita nikmati bersama hari ini.'
Mendengar hal itu, para tentara itu malu dan meminta maaf, sambil menambahkan bahwa mereka hanya menjalankan perintah atasan berdasarkan aturan yang berlaku. Demikianlah, relasi kuasa dialami petani yang jauh dari pusat kekuasaan rezim Orde Baru di Jakarta. Meskipun demikian, sampai akhir hayatnya Mbah Gatot tetap gigih menanam benih padi lokal secara organik dan mengelola Sekretariat Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Kabupaten Purbalingga yang subversif terhadap kebijakan pertanian Orde Soeharto.
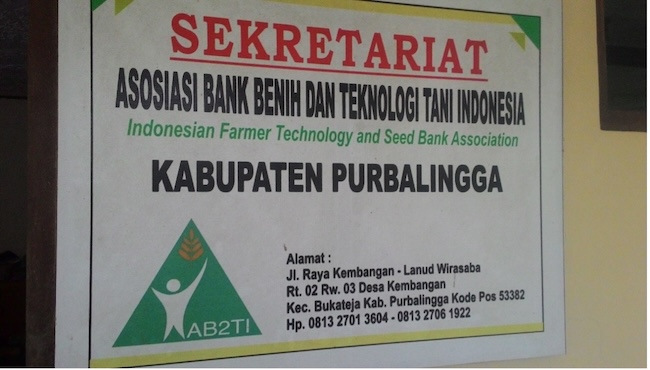
Di Jawa Timur, Desa Trawas (Kabupaten Mojokerto), bapak Cak Toko juga bercerita hal sama. Kata Cak Toko, dulu petani tidak mau menanam padi yang pemerintah perintahkan, termasuk penggunaan pupuk dan pestisida pabrikan. Sama seperti pengalaman Mbah Gatot, tentara pun mendatangi petani untuk mendesak mereka agar mematuhi ketentuan pemerintah itu. Oleh karena merasa takut, petani pun terpaksa melakukan pertanian dengan benih padi IR 36 buatan IRRI, berikut urea, phonska, ZA, KCL dan NPK yang dianjurkan. Dari semula menolak, kini mereka telah terbiasa dengan pola budidaya yang lebih praktis itu. Dalam jangka panjang, kini petani susah untuk lepas dari itu semua karena sudah menjadi kebiasaan dan terasa tidak memberatkan (praktis) sehingga gerakan pertanian organik sulit untuk mengubah perilaku budidaya itu.
Pada perspektif makro, Romo Dijkstra, SJ, Romo G. Utomo, Pr. dan Romo Agatho Elsener, OFM Cap, dalam bacaan saya, tampak memahami persoalan ini, yaitu monopoli kapitalisme global di sektor pertanian yang beriringan kepentingan dengan pemerintah. Pasca Perang Dunia Kedua dan kemerdekaan negara-negara di Amerika Latin, Asia dan Afrika, pangan adalah kebutuhan riil penduduk untuk bertahan hidup. Oleh karena skala kebutuhan ini sangat besar maka korporasilah yang menjadi mitra pemerintah. Hal inilah yang kiranya menumbuhkan aneka lembaga riset, seperti IRRI di Filipina oleh Amerika Serikat, korporasi penghasil benih tanaman pangan, penghasil pupuk dan pestisida anorganik dan juga penghasil sarana-prasarana mekanisasi pertanian baik tingkat nasional maupun internasional, seperti Monsanto. Bukan hanya itu, mereka pun kemudian menciptakan aneka benih hibrida, yang kemudian direplikasi di berbagai negara di kawasan negara-negara sedang berkembang (untuk tidak menyebut terbelakang). Ketiga pastor itu merespon perkembangan sektor pertanian ini dengan berbagi peran di Jakarta, Bantul dan Megamendung.
Terkait peran Romo Dijkstra, pada 2019 saya mendengar kisah bagaimana ia merespon monopoli korporasi internasional sepulang dari sebuah pertemuan internasional di Manila. Melalui Yayasan Bina Desa ia melakukan pelatihan terhadap banyak orang muda untuk menjadi community organizer (CO) di berbagai desa. Para aktivis CO ini lalu membentuk organisasi bernama Aliansi Petani Indonesia (API) yang aktif mendampingi para petani di banyak tempat.
Salah seorang peserta pelatihan itu kemudian menjadi aktivis lokal di sekitar Banjarnegara melalui aneka pelatihan dan pendampingan sektor pertanian, peternakan dan perkebunan dengan mengembangkan materi pelatihan dari Dr. Cho Han Kyu. Ia didatangkan ke Indonesia tiga kali dari Korea Selatan oleh Yayasan Bina Desa.[2] Dr Cho melakukan pelatihan di berbagai tempat baik di Jawa maupun Sumatera. Di Sleman saya menjumpai tiga orang yang mengikuti materi pelatihan Dr. Cho ini masih mengembangkan pertanian organik. Natural Farming adalah nama yang sering disebut oleh jaringan yang mengikuti gaya pertanian Dr. Cho ini. Sebagaimana Pak Parno di Banyumas, aktivis pertanian organik di DIY juga menjadi penggerak pertanian organik di kawasannya, bahkan menjangkau Purworejo dan Temanggung.

Secara organisatoris, para aktivis itu ada yang kemudian berintegrasi dengan jaringan lain, misalnya dengan Serikat Petani Indonesia (SPI). Para aktivis SPI di Jawa Timur beririsan afiliasi organisasi dengan Lakpesdam NU, menurut Cak Wahab di Jombang. Pada tingkat internasional, SPI bermitra dengan La Via Campesina dari Italia untuk menggerakkan pertanian organik di berbagai negara. Pertemuan internasional pernah diadakan di Sleman, Yogyakarta, termasuk mengunjungi lahan pertanian yang dikerjakan oleh para aktivis SPI di Desa Harjobinangun. Bila ditelusuri, para aktivis SPI dan API sebenarnya terkait dengan gerakan Yayasan Bina Desa.
Sudah barang tentu, mereka kemudian melakukan banyak perkembangan mandiri, sebagaimana komentar Dr. Cho kepada Pak Parno ketika keduanya bertemu di Banjarnegara, yaitu bahwa Pak Parno sudah mengembangkan banyak hal dalam hal pembuatan pupuk, nutrisi dan aneka hal lain untuk memajukan bukan hanya pertanian (farming), tetapi juga peternakan dan perkebunan. Kebutuhan lokal mendorong para aktivis berinovasi untuk menghasilkan berbagai produk organik. Ketika pupuk, pestisida, dan benih produk pabrik naik harganya, mereka tidak terpengaruh karena berdaulat pada sektor input pertanian itu. Hal senada juga dialami oleh Pak Daliman dan Pak Gimin (Kelompok Tani Organik Setyo Mandiri) di Pajangan, Bantul, yang setia berbudidaya organik, dengan formula pupuk dari Dr. Cho di atas melalui para aktivis SPI.
Gerakan Yayasan Bina Desa tersebut itu, menurut Stevanus Wangsit, bersinergi dengan gerakan Romo G. Utomo dengan Sekretariat Pelayanan Tani Nelayan Hari Pangan Sedunia (SPTN HPS).[3] Artikel Alis Windu Prasetyo dan Dionius Bismoko Mahamboro menceritakan gerakan pertanian yang dipimpin oleh Romo G. Utomo itu sejak tahun 1990, bersamaan dengan Deklarasi Ganjuran dan pendirian Paguyuban Petani dan Nelayan HPS. Mbah Gatot menyatakan bahwa ia dilatih dan menjadi jaringan dari gerakan SPTN HPS ini di kawasan Purbalingga dan sekitarnya, yang tampak pada cap kantong beras produknya: HPS. Ia menceritakan bahwa para aktivis dulu sering datang ke rumahnya dan ia pun sering datang ke DIY untuk aneka pertemuan. Stevanus Wangsit, Ketua AOI tahun 2019 dan aktivis SPTN HPS yang dekat dengan Romo G. Utomo, mengenal Mbah Gatot dengan baik. Ia mendirikan AOI bersama Indro Surono, aktivis dan alumnus IPB, yang kemudian menjadi aktivis IFOAM, sebuah federasi internasional tentang pertanian organik. Sebagaimana SPI dan AOI dengan jaringan internasionalnya, STPN HPN juga memiliki jaringan internasional sendiri.
Selain beberapa gerakan itu, ada pula aktivis yang memberi contoh bagaimana bertani organik dengan benar. Pater Agatho dan timnya melakukan hal ini di Megamendung, Cianjur, Jawa Barat, di mana ia menerima mereka yang mau belajar tentang pertanian organik dan menjual hasil pertanian ke jaringan konsumen di Bogor dan Jakarta ('pasar tertutup'). Seorang akademisi menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Romo Agatho ini subversif terhadap kebijakan budidaya pertanian pemerintah. Ia menyampaikan bahwa ada seorang dari Kementerian Pertanian yang menyarankan bahwa romo boleh menjual dan berbudidaya organik tetapi jangan terpublikasi agar tidak direpresi aparat pemerintah. Sepeninggal Romo Agatho, usaha pertaniannya masih berlanjut sampai sekarang dengan nama PT Agatho Organis Agro di Jl. Gandamanah No.40, Tugu Sel., Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sehingga karyanya masih dapat dinikmati oleh masyarakat dan para mitra.
Pembelajaran
Saya akan menyampaikan beberapa hasil pembelajaran terhadap paparan di atas. Pertama, mekanisme pertanian oleh negara untuk mewujudkan ketahanan pangan pada proses kemudian berubah menjadi bukan hanya pertanian yang digerakkan oleh negara dengan menggunakan aneka jaringan internasional dan aparat kekuasaan domestik. Mekanisme ini juga memberi peluang pagi pelaku korporasi untuk mendominasi pertanian di Indonesia melalui regulasi dan peraturan perundangan yang disahkannya.
Kedua, ketahanan pangan yang dimaksudkan untuk membantu ketersediaan pangan bagi rakyat yang semula tidak terlayani dengan baik pada penghujung Orde Lama pada gilirannya membuat petani tidak berdaulat karena dominasi penguasa dan pengusaha, birokrasi dan korporasi.
Ketiga, meskipun kedua aktor itu dominan tetapi perlawanan masih berlangsung pada tingkat akar rumput dengan membuat jejaring lokal, nasional dan internasional.
Keempat, rezim sertifikasi dan yuridis formal melayani kepentingan korporasi daripada petani karena para aktor pemerintah lebih dimudahkan dan diuntungkan pada relasi kuasa antara negara-korporasi itu dengan rakyat dan petani.
Kelima, dengan adanya poin keempat itu, kapitalisme global sektor pertanian bukan hanya bergerak pada tingkat elit semata tetapi juga berdampak pada tingkat akar rumput, sehingga semua “jejak langkah” petani tampak seperti dalam “rumah kaca” yang mudah dicermati, diintervensi dan didominasi oleh aktor pemerintah dan korporasi. Petani hanya menjadi “pekerja” pada sektor pertanian karena aspek input dan output pertanian dikuasai oleh penguasa dan pengusaha.
Keenam, apakah tidak ada jalan keluar bagi petani untuk berdaulat? Secara penuh, besar kemungkinan tidak ada jalan keluar, tetapi mereka masih dapat melakukannya secara parsial. Petani masih berpeluang bila mereka berjejaring dengan gerakan pertanian organik. Sejumlah petani dan pemulia organik di atas membuktikannya. Dominasi tidak akan pernah sepenuhnya; tinggal seperti apa dan bagaimana kegigihan petani, aktivis dan pendamping memperjuangkannya.
Suryo Adi Pramono (surya.pramana@uajy.ac.id) adalah dosen sosiologi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan koordinator tim peneliti Aliansi Organis Indonesia (AOI) 2018-2019.
Acuan
[1] Wawancara di Tretes, Mojokerto, Jawa Timur, pada tahun 2018.
[2] Bina Desa mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Dr. Cho, silakan lihat: https://www.instagram.com/yayasanbinadesa/p/DE6Ske3hy00/diakses 15 Maret 2025.
[3] Setelah Romo G. Utomo berpulang, kini SPTN HPS tidak lagi berdomisili di Ganjuran, Bantul, melainkan di: SPTN HPS D. Ronny Novianto Tegalgendu KG II 50/XI, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, 55172. Telp/Fax. 0274-380776, Email: ganjuran@indosat.net.id.











